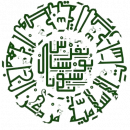Sayyid Hussein Nasr dalam Man and Nuture: Crisis of Modern Man menjelaskan, ada dua hal yang perlu dirumuskan soal krisis lingkungan. Pertama, formulasi dan upaya untuk memperkenalkan sejelas-jelasnya apa yang disebut hikmah perenial Islam tentang tatanan alam, signifikansi religius, dan kaitan eratnya dengan setiap fase kehidupan manusia. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran ekologis yang berperspektif teologis.
Krisis lingkungan kini menimpa jagad raya. Kerugian lingkungan akibat gempa dan tsunami yang menimpa Nangroe Aceh Darussalam sungguh sangat besar. Badan PBB untuk Program Lingkungan Hidup (UNEP) memperkirakan kerugian Indonesia di sektor ini saja akan mencapai 675 juta dollar AS, atau setara dengan 6 triliun rupiah.
Tak hanya itu, kerusakan lingkungan juga menjadi gejala umum hampir seluruh kawasan di Indonesia, bahkan dunia. Banjir, tanah longsor, polusi, ketidakmenentuan cuaca sering kali terjadi akhir-akhir ini. Jakarta, bahkan halaman Istana Negara pun tidak luput dari sentuhan bencana alam. Alam yang mulanya bersahabat dengan manusia, bahkan diperuntuhkan untuk manusia dalam batas-batas tertentu, justru kini bersifat destruktif dan menjadi ancaman sangat serius bagi kehidupan manusia.
Ini belum ditambah dengan krisis ekonomi, politik, budaya, dan kesehatan yang menimpa dunia ketiga, tak terkecuali Indonesia.
Semua krisis tersebut, kalau menggunakan pandangan R.F Schumacher dalam A Guide for the Perplexed (1981) adalah akibat dari krisis spiritual dan krisis perkenalan kita dengan Tuhan yang terkait dengan dimensi kepercayaan dan makna hidup. Bencana alam akibat krisis lingkungan yang silih berganti, sesungguhnya merupakan peringatan bagi segenap manusia untuk mereoreintasi hidup mereka yang terus saja merusak alam. Semua itu terjadi karena perilaku manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.
Padahal, anjuran melestarikan lingkungan merupakan ajaran yang sangat purba dan fundamental dari agama. Ini dapat kita cermati dari kasus kejatuhan Adam ke muka bumi. Konon dalam doktrin legend of the fall dijelaskan, Adam disebut tersingkir dari surga yang penuh estetika, kedamaian, kerindangan, dan subur ke muka bumi yang gersang, karena dia tidak mengindahkan ajaran Tuhan, yakni kearifan ekologis. Adam dan Hawa (Eva) memakan dan merusak buah dan pohon kekekalan (QS. 2: 35-39). Dari sini dapat dipahami bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan doktrin purba dari agama.
Doktrin tersebut telah menempatkan kesadaran dan pemeliharan ekologi sebagai hal utama setelah teologi. Namun seiring perkembangan manusia, ajaran tersebut makin terlupa dan tersingkir dari pola kehidupan. Perusakan lingkungan, pembakaran hutan, penebangan pohon secara liar, dan eskploitasi kekayaan alam secara besar-besaran dianggap absah belaka. Itu semua terkadang dilakukan dengan dalih bahwa alam semesta telah dicipta semata-mata untuk kepentingan manusia.
Manusia yang mendapat mandat sebagai khalifah muka bumi seolah-olah diperkenankan untuk melakukan eksploitasi dan pemerkosaan atas semesta alam. Padahal, konsep khalîfah (aktif memakmurkan bumi) dalam doktrin Islam tidak pernah otonom. Di samping sebagai khalîfah, manusia juga bagian dari hamba Allah (penerima rambu-rambu Allah) yang seyogyanya melestarikan dan memanifestasikan ajaran dan sifat-sifat Tuhan di muka bumi.
Karena itu, perusakan semesta alam sama sekali tidak punya landasan teologis. Memelihara lingkungan, justru suatu panggilan teologis yang sangat mulia. Kita sudah semestinya memikirkan kembali aspek kerusakan lingkungan yang sedemikian parah, lalu melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan kehidupan.
Untuk langkah tersebut, usaha menapak tilas pola hidup orang-orang bijak dan para mistikus Islam menjadi sangat berguna. Sebab, di sana akan kita temukan betapa mereka begitu cinta terhadap alam dan lingkungannya. Sa’di misalnya, penyair Persia itu, suatu kali bersenandung: “Aku bersuka cita dengan kosmos/aku juga mencintai seluruh dunia/karena dunia adalah milik-Nya.” Penyair lainnya, Yusuf Emre, secara puitis menyimbolkan fakta ekologis dengan realitas alam surgawi, “Semua sungai yang ada di surga/mengalir dengan kata Allah, Allah/Dan setiap burung Bulbul, bercumbu dan melantunkan nada: Allah, Allah!”
Eco-Theology
Sayyid Hussein Nasr dalam Man and Nuture: Crisis of Modern Man seperti dikutip Ihsan A. Fauzi (1994) menjelaskan, ada dua hal yang perlu dirumuskan soal krisis lingkungan. Pertama, formulasi dan upaya untuk memperkenalkan sejelas-jelasnya apa yang disebut hikmah perenial Islam (hikmah khalidah/scientia sacra, philosophia perennis) tentang tatanan alam, signifikansi religius, dan kaitan eratnya dengan setiap fase kehidupan manusia. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran ekologis yang berperspektif teologis (eco-theology), dan jika perlu, memperluas wilayah aplikasinya sejalan dengan prinsip syariat itu sendiri.
Dalam kerangka itulah, membangun teologi berbasis kesadaran dan kearifan ekologis—yang kerap disebut eco-theology—merupakan kebutuhan mendesak yang tak bisa kita tawar-tawar lagi. Untuk keperluan itu, ada tiga hal yang perlu ditegaskan di sini. Pertama, menempatkan persoalan lingkungan sebagai bagian dari agama. Dalam kitab al-Muwâfaqât, Abu Ishaq al-Syatibi membagi tujuan hukum Islam (maqâshid al-syarîah) menjadi lima hal: 1) penjagaan agama (hifdz al-dîn), 2) memelihara jiwa (hifdz al-nafs), 3) memelihara akal (hifdz al-‘aql), 4) memelihara keturunan (hifdz al-nasl), dan 5) memelihara harta benda (hifdz al-mâl). Pertanyaan kita: di mana posisi pemeliharaan ekologis (hifdz al-`âlam) dalam Islam?
Untuk menjawab itu, Yusuf al-Qardlawi dalam Ri’âyatu al-Bi’ah fi al-Syarî’ati al-Islâmiyyah (2001) menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga maqâshidus syarî’ah yang lima tadi. Selain al-Qardlawi, al-Syatibi juga menjelaskan bahwa sesungguhnya maqâshidus syarî’ah ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, di mana bila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak berdiri, sehingga berakibat pada kerusakan dan hilangnya kenikmatan perikehidupan manusia.
Kedua, ajaran Taoisme tentang Yin-Yang juga dapat memberi kearifan.
Yang biasanya digambarkan sebagai agresif, maskulin, kompetitif, dan rasional. Sementara Yin dilukiskan konservatif, intuitif, kooperatif, feminin, dan responsif. Dalam Taoisme, Yin-Yang harus berjalan secara sejajar dan seimbang, sehingga keharmonisan antara makrokosmos dan mikrokosmos terwujud. Kenyataan kita lebih suka berpikir rasional, linear, mekanistik, dan materialistik perlu diseimbangkan dengan pengetahuan yang intuitif, non-linear, dan koordinatif, sebagai perwujudan Yin (kearifan ekologis). Ajaran Taoisme ini rasanya penting untuk diadopsi guna menjawab krisis ekologis yang terus mengancam kita.
Terakhir, kita mungkin juga perlu mendengar fatwa Charlene Spretnak dalam TheSpiritual Dimension of Green Politics. Di situ dia menekankan pentingnya mengembangkan green politics (politik hijau); gerakan politik yang sadar ekologi. Kebijakan-kebijakan sosial-politik-ekonomi kita sudah saatnya mempertimbangkan soal lingkungan hidup. Sudah waktunya para pejabat negara, politisi, dan partai-partai politik menyuarakan pentingnya kesadaran akan politik hijau atau politik ekologis (ecological politics) ini. []
Hatim Gazali, peneliti Community for Religion and Social Engineering (CRSe) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.